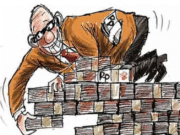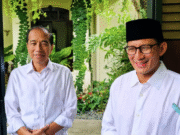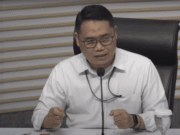Beberapa tahun lalu, saya pernah menemani istri dalam kunjungan ke berbagai madrasah di sebuah kabupaten yang terletak di pedalaman Kalimantan. Saat itu, istri saya sedang terlibat dalam program nasional yang bertugas melakukan survei, wawancara, serta mengumpulkan masukan untuk peningkatan kualitas madrasah di daerah tersebut. Perjalanan itu sudah cukup lama, tetapi ada satu pengalaman yang masih sangat melekat di ingatan saya hingga saat ini.
Saya masih ingat betul kondisi madrasah-madrasah yang kami kunjungi. Sebagian besar bangunan terbuat dari papan kayu. Di salah satu sekolah, satu ruangan dibagi menjadi dua kelas. Dua kegiatan belajar-mengajar berlangsung bersamaan, hanya dipisahkan oleh papan. Suara guru dan siswa saling bersahutan, tumpang tindih, hingga sulit dibedakan mana yang sedang mengajar dan mana yang menjawab. Saya membayangkan betapa sulitnya anak-anak di sana berkonsentrasi dan memahami pelajaran dengan baik.

Kondisi fisiknya pun memprihatinkan. Awalnya saya berpikir, mungkin ini hanya pandangan saya sebagai orang luar—seseorang yang datang dengan standar berbeda. Mungkin bagi masyarakat setempat, kondisi sekolah seperti itu sudah dianggap cukup layak. Namun di sisi lain, hati kecil saya sulit menerima kenyataan itu begitu saja.
Janji Revitalisasi dari Pemerintah
Pertanyaan yang muncul di benak saya waktu itu sederhana: Mengapa pemerintah tidak merevitalisasi madrasah seperti ini agar lebih layak? Bukankah madrasah, meski banyak yang berstatus swasta, juga berperan besar membantu negara mencerdaskan kehidupan bangsa?
Karena itu, ketika Presiden Prabowo mencanangkan program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai bagian dari program strategis pemerintah, saya menyambutnya dengan optimisme. Bagi saya, program ini adalah jawaban konkret atas kegelisahan yang pernah saya rasakan bertahun-tahun lalu. Revitalisasi satuan pendidikan bukan hanya soal memperbaiki bangunan, melainkan juga simbol keseriusan negara memastikan setiap anak—di manapun mereka berada—bisa belajar di lingkungan yang layak.

Komitmen presiden itu kemudian dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025, yang mengamanatkan sejumlah kementerian untuk bersama-sama menjalankan program revitalisasi sekolah. Artinya, tanggung jawab ini bersifat lintas sektor dan tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga saja.
Arah dan Cakupan Program
Secara garis besar, program revitalisasi satuan pendidikan terbagi menjadi dua kelompok besar, dengan pendekatan dan lembaga pelaksana yang berbeda. Pertama, revitalisasi sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini berfokus pada satuan pendidikan umum, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola. Artinya, pihak sekolah dan masyarakat setempat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga pengawasan. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki sarana fisik, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sekolah.
Berdasarkan data dari acara “Sosialisasi Calon Penerima Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2025 Angkatan 3”, yang ditayangkan di kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar pada 22 Agustus 2025, pemerintah mengalokasikan total Rp17,15 triliun untuk program ini. Program revitalisasi sekolah menyasar 10.440 satuan pendidikan, dengan komposisi 78% sekolah negeri dan 22% sekolah swasta. Fokus terbesar berada pada Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 4.053 sekolah dengan anggaran Rp4,89 triliun.

Selanjutnya, SMP mendapat alokasi untuk 2.753 sekolah dengan anggaran Rp5,15 triliun, SMA sebanyak 1.382 sekolah dengan Rp2,94 triliun, dan SMK sebanyak 767 sekolah dengan Rp2,78 triliun. Untuk PAUD, terdapat 1.270 lembaga dengan total Rp0,65 triliun, sementara SLB dan SKB masing-masing mendapat alokasi Rp0,55 triliun dan Rp0,15 triliun. Seluruh data ini berasal dari hasil sinkronisasi DAK Fisik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah—langkah nyata memperkuat layanan pendidikan di berbagai jenjang.
Kedua, revitalisasi madrasah yang ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Agama. Program ini dilaksanakan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai tindak lanjut langsung dari Inpres Nomor 7 Tahun 2025. Jika program Kemendikdasmen lebih menekankan swakelola berbasis sekolah, program PHTC menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur madrasah melalui mekanisme proyek fisik yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dengan dukungan data dan koordinasi dari Kemenag.

Menurut keterangan resmi Kementerian PU, program ini mencakup total 2.120 madrasah di seluruh Indonesia, dibagi menjadi dua tahap: Tahap 1 mencakup 179 madrasah di 5 provinsi sejak Oktober 2024, dan Tahap 2 mencakup 1.941 madrasah di 37 provinsi sejak Januari 2025. Dengan demikian, kedua program ini—meski berbeda pelaksana dan pendekatan—memiliki tujuan yang sama: menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak dan merata bagi seluruh anak Indonesia, baik di sekolah maupun madrasah.
Tantangan di Lapangan
Dari pengamatan dan pengumpulan data terbatas yang saya lakukan di beberapa kabupaten, tampak bahwa pelaksanaan program ini belum sepenuhnya merata. Dari tiga kabupaten yang saya monitor, jumlah sekolah penerima program berbeda cukup jauh. Ada satu kabupaten yang memperoleh jatah 26 sekolah, kabupaten lain hanya 4, bahkan satu kabupaten hanya 2 sekolah. Kondisi serupa juga terlihat pada madrasah. Ada kabupaten dengan sejumlah madrasah yang mendapat program revitalisasi dan ada yang tidak mendapat sama sekali. Dari dua kabupaten yang menerima program tersebut, hingga tulisan ini disusun, pelaksanaannya belum dimulai.

Perbedaan ini mengindikasikan bukan hanya soal distribusi anggaran, melainkan juga perbedaan kapasitas kelembagaan dan kesiapan teknis di daerah. Kabupaten—dengan sumber daya manusia yang terbatas atau kurang memahami mekanisme pengusulan program—sering kali tertinggal, meskipun memiliki kebutuhan mendesak. Selain itu, fokus revitalisasi yang masih dominan pada aspek fisik kadang belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan kapasitas nonfisik, seperti pelatihan guru, digitalisasi pembelajaran, atau tata kelola aset sekolah. Padahal, bangunan yang baik hanya akan bermakna jika diisi oleh proses belajar yang hidup dan adaptif.
Isu Strategis dan Arah Penguatan ke Depan
Dari sekelumit gambaran di lapangan, ada beberapa hal strategis yang patut dicermati—bukan sebagai kritik, melainkan sebagai bahan perbaikan agar program ini semakin efektif dan berkelanjutan. Pertama, penyelarasan data dan koordinasi antarlembaga. Program revitalisasi melibatkan banyak pihak, mulai dari Kemendikdasmen, Kemenag, Kemen-PU, hingga pemerintah daerah. Karena itu, dibutuhkan sistem komunikasi dan integrasi data yang lebih sinkron antara pusat dan daerah. Dengan penyelarasan yang baik, seluruh satuan pendidikan, termasuk madrasah di wilayah terpencil, dapat memperoleh manfaat secara proporsional.
Kedua, penguatan sistem prioritas berbasis kebutuhan nyata. Perbedaan jumlah sekolah penerima program di setiap kabupaten menunjukkan masih perlunya pendekatan berbasis data kondisi lapangan. Dengan pemetaan kebutuhan yang lebih akurat, daerah dengan tingkat kerusakan sarpras tinggi bisa menjadi prioritas, tanpa mengabaikan pemerataan antarwilayah. Ketiga, peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan di daerah. Program besar seperti ini memerlukan kemampuan perencanaan, pelaporan, dan pengawasan yang kuat di tingkat lokal. Pemerintah dapat memperkuat peran pendamping atau fasilitator lokal agar daerah dengan SDM terbatas tetap mampu mengeksekusi program dengan baik.

Keempat, keseimbangan antara revitalisasi fisik dan nonfisik. Revitalisasi seharusnya tidak berhenti pada bangunan, tetapi juga memperbarui ekosistem pembelajaran di dalamnya. Misalnya, dengan melibatkan sekolah penerima dalam pelatihan manajemen aset, pengembangan kurikulum kontekstual, dan penerapan teknologi pembelajaran. Kelima, memperkuat kesejahteraan guru sebagai bagian dari revitalisasi pendidikan. Pembangunan fisik sekolah dan madrasah tidak akan bermakna tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan guru, terutama bagi guru non-ASN di madrasah yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di daerah. Pemerintah perlu memastikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dilakukan tepat waktu, tidak dirapel, serta memperluas dukungan kesejahteraan lainnya agar para guru dapat mengajar dengan tenang dan bermartabat.
Akhirnya, revitalisasi satuan pendidikan sejatinya bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Ia adalah simbol kehadiran negara di ruang-ruang kecil di pelosok negeri—tempat anak-anak menanam mimpi, guru menyalakan harapan, dan masa depan bangsa disiapkan. Semoga kali ini, harapan yang dulu hanya terselip di tengah derit papan dan suara dua kelas yang bersahutan itu benar-benar menemukan jawabannya.