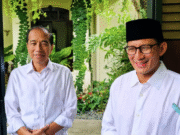Orkes Hujan di Langit Senja
Rendra duduk di balik jendela kamar kosnya, menatap langit senja yang berlapis awan kelabu. Di antara kabut tipis, rintik hujan turun perlahan, seperti not-not lembut dari orkes yang dimainkan langit untuk bumi. Oktober datang dengan aroma tanah lembap dan udara yang mulai menggigil pelan.
Sudah tiga bulan ia tinggal di kota ini. Kota yang katanya tak pernah benar-benar sepi, tapi baginya justru terasa sunyi. Setiap sore, saat langit mulai memerah, Rendra punya kebiasaan menulis puisi di buku lusuh peninggalan ayahnya. Halaman terakhir berisi tulisan tangan sang ayah: “Hujan bukan tentang jatuh, tapi tentang kembali.” Ayahnya meninggal dua tahun lalu karena serangan jantung, tepat di bawah langit yang juga sedang hujan. Sejak itu, Rendra selalu merasa hujan punya bahasa sendiri, bahasa yang bisa berbicara dengan kenangan.
Sore ini, seperti sore-sore sebelumnya, ia berjalan ke taman kecil di belakang kampus. Rumputnya basah, bangkunya dingin, tapi di situlah ia merasa paling dekat dengan dirinya sendiri. Di taman itu, ia pertama kali bertemu Aluna. Perempuan berambut hitam panjang dengan mata teduh yang seperti menyimpan langit di dalamnya. Mereka bertemu saat sama-sama berteduh di bawah pohon flamboyan. Saat itu Aluna berkata, “Hujan selalu memainkan musik yang sama, tapi setiap orang mendengarnya berbeda.”
Sejak saat itu, Rendra mulai mendengarkan hujan dengan cara lain, seperti mendengarkan puisi yang dibisikkan waktu. Namun kini, Aluna sudah tidak ada lagi. Ia pergi sebulan lalu, berpindah ke kota lain untuk melanjutkan studi musiknya. Tak ada perpisahan yang manis, hanya pesan singkat: “Jangan berhenti menulis, Ren. Aku akan mendengarkan hujan yang sama di langit yang berbeda.”
Rendra masih menyimpan pesan itu. Kadang dibacanya ulang, bukan untuk mengingat, tapi untuk merasa bahwa jarak tak selalu berarti kehilangan. Hujan mulai menebal. Rendra menutup bukunya dan memandangi langit. Di antara kilat yang samar, ia membayangkan Aluna berdiri di bawah atap, memainkan biolanya dengan jemari yang basah. Ia bisa mendengar melodi yang lembut itu, membaur dengan suara hujan yang jatuh di atap seng.
Lalu, entah mengapa, hari itu terasa berbeda. Dari ujung taman, terdengar suara biola sungguhan. Rendra menoleh cepat. Di bawah gazebo kecil, seseorang sedang memainkan lagu yang sangat ia kenal, “Orkes Hujan di Langit Senja”, karya Aluna sendiri. Ia berlari kecil mendekat. Di sana, berdiri seorang perempuan mengenakan mantel krem, wajahnya sebagian tertutup topi hujan. Tapi dari cara ia memainkan senar, Rendra tahu: itu dia.
“Aluna?” suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Perempuan itu berhenti bermain, menatapnya, lalu tersenyum. “Kau masih mendengarkan hujan, ya?” Rendra nyaris tak percaya. “Kupikir kau sudah pergi jauh.” “Aku pergi, tapi tidak sepenuhnya. Kadang, kita hanya perlu jarak untuk menemukan melodi yang hilang.” Ia menurunkan biolanya pelan. “Aku rindu memainkan lagu ini bersamamu.”
Rendra mendekat, air hujan menetes di rambutnya. “Kau tahu, aku menulis banyak puisi setelah kau pergi. Tapi tak satu pun yang selesai. Seolah setiap kalimat berhenti di ujung senja.” Aluna tersenyum samar. “Mungkin karena kau menulis untuk mengingat. Padahal menulis seharusnya untuk melepaskan.”
Rendra terdiam. Hujan terus turun, membentuk tirai air di antara mereka. Dalam remang senja, wajah Aluna tampak tenang, seperti sosok dari mimpi yang lama tak dikunjungi. “Kenapa kau kembali?” tanyanya pelan. Aluna menatap langit. “Karena aku ingin memainkan hujan bersamamu sekali lagi. Setelah itu, mungkin aku akan benar-benar pergi.”
Hening. Angin membawa aroma tanah dan daun basah. Di bawah langit yang menua, mereka duduk berdampingan di gazebo sempit. Aluna mengangkat biolanya, Rendra membuka bukunya. Tanpa aba-aba, musik dan kata mulai mengalun bersamaan—melodi yang menggetarkan udara, dan puisi yang menyalakan makna di setiap tetes hujan.
Rendra menulis:
“Senja tak pernah menolak hujan,
karena di dalam derasnya, ada lagu rindu yang tak selesai.
Langit pun tahu, setiap pertemuan adalah cara waktu menebus kehilangan.”
Aluna berhenti bermain. Air mata menetes di pipinya, bercampur dengan rintik hujan. “Indah sekali,” bisiknya. Rendra tersenyum. “Kau tahu, mungkin ayahku benar. Hujan bukan tentang jatuh, tapi tentang kembali. Seperti kamu hari ini.”
Aluna menatapnya lama. “Aku tidak kembali untuk tinggal, Ren. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak berhenti menulis.” Rendra menunduk, menahan sesuatu yang sesak di dadanya. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi semua kata seakan tenggelam dalam gemuruh langit.
Beberapa menit kemudian, hujan mulai reda. Senja perlahan memberi tempat pada malam. Aluna berdiri, menyampirkan biolanya, lalu berkata lirih, “Kalau suatu hari nanti hujan turun tanpa suara, dengarkan baik-baik. Mungkin aku sedang memainkan lagu ini dari langit.” Rendra menatap langkahnya menjauh. Aluna berjalan ke arah barisan pohon, lalu lenyap di balik kabut.
Tinggal Rendra sendirian di gazebo, ditemani sisa hujan yang menetes di atap seng. Tapi entah kenapa, kali ini kesendirian terasa damai. Ia tahu, Aluna benar—ada melodi yang hanya bisa dimainkan ketika seseorang pergi. Ia membuka bukunya sekali lagi dan menulis kalimat penutup:
“Hujan tak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah dari langit ke hati.”
Lalu ia menutup buku itu, menatap langit malam yang mulai menampakkan satu bintang di ujung awan. Barangkali, di langit yang sama, Aluna sedang menatap bintang yang sama pula. Malam itu, hujan berhenti, tapi suara orkesnya masih bergema, bukan di udara, melainkan di dada Rendra. Dan di bawah langit Oktober yang lembut, ia akhirnya mengerti: setiap kehilangan hanyalah lagu yang menunggu untuk dimainkan kembali.