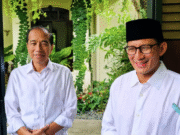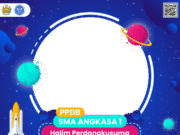KEBIJAKAN pemerintah yang diumumkan pada Senin (16/12) siang mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya pepesan kosong belaka. Narasi pengecualian terhadap objek bahan pokok sedianya bukan hal baru. Kebaruan hanya ada dari komoditas gula industri, tepung terigu, dan Minyakita yang pungutan PPN-nya tetap 11%.
Dengan demikian, pada dasarnya kenaikan tarif PPN di tahun depan tetap akan berdampak pada sebagian besar kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah. Alhasil, muncul risiko inflasi yang tinggi di tahun depan dan menekan perekonomian, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.
“Hal ini akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan. Kementerian Keuangan hari ini pandai sekali bermain kata-kata. Seakan-akan Pemerintah dan DPR hari ini mendukung kebijakan progresif bahwa semua barang pokok dikecualikan PPN. Padahal, kebijakan pengecualian itu sudah ada sejak tahun 2009. Kenyataannya, PPN tetap naik untuk hampir semua komoditas yang dikonsumsi masyarakat bawah,” ujar Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar melalui keterangan tertulis, Senin (16/12).
Dari hitungan Celios, kata dia, kenaikan PPN menjadi 12% menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan, memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan.
PPN 12% Berdampak Luas
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menuturkan, kenaikan tarif PPN menjadi 12% berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat termasuk peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.
“Bahkan deterjen dan sabun mandi apa dikategorikan juga sebagai barang orang mampu? Narasi pemerintah semakin kontradiksi dengan keberpihakan pajak. Selain itu kenaikan PPN 12% tidak akan berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak, karena efek pelemahan konsumsi masyarakat, omzet pelaku usaha akan mempengaruhi penerimaan pajak lain seperti PPh badan, PPh 21, dan bea cukai,” tuturnya.
Selain itu paket kebijakan ekonomi pemerintah cenderung berorientasi jangka pendek dan tidak ada kebaruan yang berarti. Insentif dan stimulus pemerintah hampir mengulang dari insentif yang sudah ada. PPN perumahan DTP, PPN kendaraan listrik dan PPh final UMKM 0,5% sudah ada sebelumnya.
“Bentuk bantuan juga bersifat temporer seperti diskon listrik dan bantuan beras 10kg yang hanya berlaku 2 bulan, sementara efek negatif naiknya tarif PPN 12% berdampak jangka panjang,” kata Bhima.
Pemerintah juga memberikan insentif PPN DTP 3% untuk kendaraan Hibrida. Ini semakin membuat kontradiksi, keberpihakan pemerintah ternyata jelas pro terhadap orang kaya karena kelas menengah justru diminta membeli mobil hibrida di saat ekonomi melambat.
“Harga mobil hibrida pastinya mahal, dan ini cuma membuat konsumen mobil listrik EV yang notabene kelompok menengah atas beralih ke mobil Hybrid yang pakai BBM. Bagaimana bisa ini disebut keberpihakan pajak?” ujar Bhima.
Dia menambahkan momentum pengumuman kenaikan PPN 12% ini juga dinilai tidak tepat, karena dilakukan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, saat produsen cenderung menaikkan harga lebih tinggi dari biasanya. Hal itu berpotensi memperburuk beban pengeluaran masyarakat di tengah lonjakan konsumsi akhir tahun.
Pemerintah, menurutnya, berkukuh agar kebijakan itu tetap dilanjutkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian. Alternatif lain, seperti memperluas basis pajak, penerapan pajak kekayaan dan memberantas celah penghindaran pajak, sebetulnya dapat lebih efektif meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat.
Sedangkan Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengungkapkan, pembedaan tarif PPN di tahun depan tak memiliki cantolan hukum yang matang. Itu karena rezim PPN di Indonesia menganut tarif tunggal, alih-alih multitarif.
“Kebijakan tarif PPN Indonesia masih menganut single tarif. Pemberian insentif berupa Ditanggung Pemerintah (DTP) bisa dicabut kapan saja dan menimbulkan ketidakpastian tarif PPN barang-barang tersebut kelak. Kebijakan ini justru bisa melanggar UU tentang PPN baik di HPP ataupun UU lainnya. Klaim Sri Mulyani dan Airlangga kenaikan tarif PPN untuk mematuhi UU HPP hanya omong kosong belaka,” kata Nailul.
“Dampak kenaikan tarif PPN terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga negatif. Ketika tarif PPN di angka 10 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 5 persen-an. Setelah tarif meningkat menjadi 11 persen terjadi perlambatan dari 4,9 persen (2022) menjadi 4,8 persen (2023). Diprediksi tahun 2024 semakin melambat,” tambahnya.
Karenanya, Celios merekomendasikan kenaikan PPN sebaiknya dikaji kembali agar tidak memperburuk kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah kondisi sosial-ekonomi yang masih rentan. (Mir/M-3)