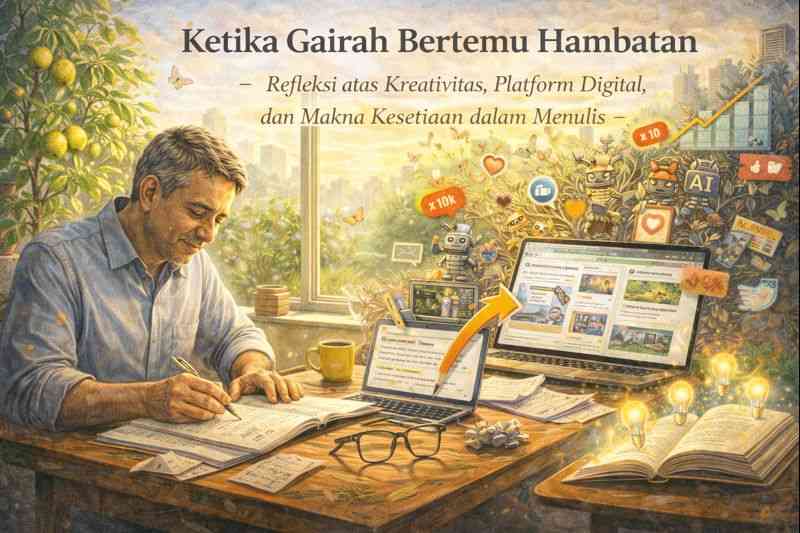Ketika Gairah Bertemu Hambatan: Refleksi atas Kreativitas, Platform Digital, dan Makna Kesetiaan dalam Menulis
Di antara detak jantung yang tidak selalu teratur dan halaman kosong yang diam menantang, terletak pertanyaan abadi tentang kesetiaan pada panggilan menulis. Bagaimana mempertahankan integritas kreatif ketika tubuh lelah, algoritma tak ramah, dan tuntutan dunia digital seolah mengaburkan makna berkarya?
Tulisan ini adalah meditasi atas pertarungan antara idealisme dan realitas, sebuah upaya untuk menemukan kembali esensi menulis di tengah gemuruh zaman, di antara semangat yang membara dan fisik yang tergerus/terbatas.
Paradoks Antara Semangat dan Kelemahan Fisik
Sepekan terakhir, hipertensi yang kambuh menjadi pengingat tegas akan keterbatasan tubuh manusiawiku. Di tengah gejolak ide yang mengalir deras, energi fisik dan mental justru merosot, menciptakan jurang antara hasrat berkarya dan kemampuan untuk merealisasikannya.
Naskah 340 halaman yang dipesan seorang pastor, artikel tentang hukum adat, atau bahkan catatan harian sederhana, terpaksa tertunda bukan karena ketiadaan minat, melainkan ketidakseimbangan antara jiwa yang membara dan raga yang letih.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah produktivitas kreatif harus selalu diukur oleh kecepatan? Dalam budaya yang mendewakan output, kita kerap lupa bahwa proses berkarya yang bermakna membutuhkan ruang untuk bernapas, baik secara fisik maupun spiritual.
Kelemahan tubuh, dalam konteks ini, bukanlah kegagalan, melainkan undangan untuk merenung: kapan kita perlu berhenti sejenak, memulihkan diri, dan kembali dengan kejelasan pikiran?
Indonesiadiscover.com dan Tantangan Ekosistem Kreatif Digital
Platform digital seperti Indonesiadiscover.com, dengan 5,8 juta anggota, menawarkan ruang demokratis bagi setiap suara. Namun, di balik kemudahan akses, tersembunyi dinamika kompleks: algoritma yang memprioritaskan konten viral, sensor otomatis yang membatasi diskusi kritis, serta sistem K-Rewards yang kerap kali tidak selaras dengan kualitas substansi.
Tulisan reflektif tentang isu sosial atau filosofis seringkali kalah pamor dibanding konten instan, meski keduanya sama-sama membutuhkan ruang untuk didengar.
Ketidakseimbangan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan tantangan etis. Bagaimana memastikan platform digital tidak hanya menjadi pasar bagi konten yang menghibur, tetapi juga ruang bagi pemikiran yang mengganggu status quo?
Di sinilah peran penulis, pembaca, dan pengelola platform bertemu: menciptakan ekosistem yang menghargai kedalaman sekaligus kecepatan, tanpa mengorbankan salah satunya demi pertumbuhan semu.
Pelajaran dari Sebatang Pohon Jambu Liar
Di pekarangan rumah kami, sebatang pohon jambu liar tumbuh di tanah yang bukan milik kami. Selama bertahun-tahun, ia dirawat tanpa pamrih (disiram di musim kemarau, dilindungi dari angin kencang juga dari cakaran ayam) hingga kini memberikan buah melimpah yang dinikmati manusia dan kalong.
Kisahnya mengajarkan bahwa kesetiaan pada proses, meski tanpa jaminan hasil, sering kali membuahkan makna yang tak terduga. Tidak ada algoritma yang mengukur nilainya, tidak ada reward instan, hanya ketekunan yang diam-diam mengubah tanah gersang menjadi sumber kehidupan.
Metafora ini relevan bagi para penulis di era digital. Di tengah tekanan untuk mendapat label “Pilihan” atau viral di media sosial, mudah sekali lupa bahwa karya bermakna lahir dari konsistensi yang tak selalu terlihat.
Seperti pohon jambu, kita perlu berani tumbuh di tempat yang tak nyaman, merawat ide-ide yang mungkin tak segera diapresiasi atau kalaupun apresiasi bisa dengan kritik yang membangun agar bertumbuh dan berkembang bersama, sambil percaya bahwa kejujuran dalam berkarya akan menemukan jalannya sendiri, entah melalui platform besar atau blog pribadi yang sepi pengunjung.
Menulis sebagai Aktivitas Spiritual: Antara Ego dan Kejujuran
Latar belakang pendidikan filsafat-teologi membentuk kebiasaan menulis saya dengan pendekatan reflektif-meditatif. Setiap kata diupayakan menjadi jembatan antara pengalaman konkret dan pencarian makna universal, ada pendalaman, pengendapan nilai.
Namun, di tengah arus konten cepat saji, gaya semacam ini kerap dianggap “terlalu berat” atau “tidak praktis” alias kuno. Tantangannya bukan hanya pada algoritma, melainkan pada budaya membaca yang semakin permisif terhadap kedangkalan, sebuah paradoks di era informasi berlimpah.
Belum lagi kalau kita mau jujur, anak-anak sejak dini sudah diajari nonton TikTok, Instagram dan platform hiburan lainnya dengan durasi 1-3 menit. Sejak dini anak-anak sudah dibiasakan untuk malas membaca, senang yang hiburan tapi yang ilutif, tidak mengajarkan kerja keras, tapi menjadi penikmat pasif yang justru aktif menghabiskan kuota alias isi dompet orang tua. Salah siapa? Salah zaman? Salah teknologi? Bukan mencari kesalahan, tetapi mari kita mencari terobosan agar kita peduli dengan generasi yang berisi (berkat membaca) bukan yang hanya menonton hasil kreasi ilutif. Hidup ini bukan demi konten. Tapi buatlah konten demi hidup.
Di sinilah ujian terbesar bagi penulis seperti saya: mempertahankan integritas intelektual tanpa terjebak dalam keinginan untuk disukai. Seperti kisah janda miskin dalam Injil (Markus 12:41-44), nilai sebuah karya terletak pada ketulusan hati yang mengalirkannya, bukan pada jumlah pembaca atau likes.
Menulis, dalam perspektif ini, menjadi aktivitas spiritual, sebuah persembahan yang tulus, meski harus berdiri di tepi arus utama.
Menuju Ekosistem Menulis yang Berkeadilan
Indonesiadiscover.com, dengan 5,8 juta anggota, adalah cermin dinamika literasi Indonesia. Namun, ketimpangan pengakuan masih terasa jelas. Fahruddin, seorang penulis dengan gaya staccato dan analisis mendalam tentang isu lingkungan dan sosial, kerap kesulitan mendapat label “Pilihan” atau masuk headline, meski tulisannya kaya data dan perspektif.
Sementara itu, konten berbasis AI (dengan struktur rapi namun minim jiwa) sering mendominasi ruang unggulan. Situasi ini memicu pertanyaan: apakah algoritma justru menggerus ruang bagi karya yang membutuhkan kepekaan dan kedalaman?
Di sisi lain, suara kritis dari penulis senior bercentang biru seperti Felix Tani dan Raja Lubis tetap menjadi penyeimbang vital. Mereka membuktikan bahwa tulisan bernas masih mampu bertahan, meski harus berhadapan dengan hiruk-pikuk konten instan.
Tantangan ke depan adalah menciptakan sistem yang tidak hanya menghargai popularitas sesaat, tetapi juga memberi ruang bagi karya yang menantang, mengedukasi, dan menginspirasi dalam jangka panjang.
Ini bukan kritik terhadap teknologi, melainkan ajakan untuk merefleksikan ulang: bagaimana merancang algoritma dan kebijakan editorial yang memuliakan keragaman perspektif, bukan hanya keseragaman yang menguntungkan secara komersial?
Penutup: Menulis sebagai Bentuk Perlawanan
Tulisan ini, yang awalnya lahir dari pergulatan antara kelelahan fisik dan hasrat intelektual, pada akhirnya adalah bentuk perlawanan.
Perlawanan terhadap budaya instan yang mengukur nilai karya dari metrik semata, terhadap narasi bahwa produktivitas harus selalu linier, dan terhadap ilusi bahwa platform digital dapat sepenuhnya menggantikan hubungan manusia dengan kata-kata.
Seperti pohon jambu yang bertahan di tanah asing, para penulis perlu berani menumbuhkan ide-ide mereka di antara ketidakpastian, sambil tetap setia pada panggilan untuk menyuarakan kebenaran, sekecil apa pun resonansinya.
Di tengah anomali cuaca dan gejolak teknologi, ada satu kepastian: selama masih ada napas untuk merenung dan jari yang mampu menari di atas papan ketik, setiap kata yang tulus adalah benih perubahan.
Menulis, dalam esensinya, bukanlah tentang menjadi yang terlihat, melainkan tentang menjadi yang bermakna.