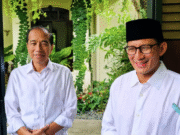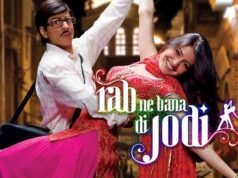Bakpia Pathok: Simbol Akulturasi Budaya di Yogyakarta
Bakpia bukan sekadar camilan manis isi kacang hijau. Di balik kulitnya yang lembut, tersimpan kisah akulturasi antara budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, bakpia berasal dari resep kue Tionghoa bernama bakpia, bak berarti daging babi, dan pia berarti kue pipih isi. Namun, saat dibawa ke nusantara oleh perantau Tionghoa pada awal abad ke-20, resepnya disesuaikan dengan selera lokal.
Di kawasan Pathuk, Yogyakarta, daging babi diganti dengan isian kacang hijau agar bisa dinikmati oleh masyarakat muslim. Dari sinilah muncul nama “Bakpia Pathok” yang kini menjadi ikon oleh-oleh khas Yogyakarta. Seiring waktu, bakpia berkembang dengan berbagai varian rasa seperti keju, cokelat, hingga durian.
Jika kamu ingin mencicipi cita rasa bakpia legendaris, bisa mampir ke Bakpia Legendaris Jelambar di Jakarta Barat, atau mencoba Bakpia Kukus Tugu Jogja yang kini juga tersedia di berbagai kota dan layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood.
Cenil: Si Kenyal yang Penuh Warna dan Sejarah Panjang
Siapa sangka, jajanan kecil berwarna cerah bernama cenil ternyata sudah ada sejak zaman Mataram Kuno. Kue ini bahkan disebut dalam Serat Centini tahun 1814, menandakan bahwa cenil merupakan bagian dari warisan kuliner yang telah berusia ratusan tahun.
Asalnya dari Pacitan, di masa ketika beras sulit ditemukan dan masyarakat harus mencari alternatif makanan pokok. Dari ketela pohon, lahirlah cenil, camilan kenyal yang dulu menjadi penyelamat. Warna-warnanya yang mencolok ternyata bukan dari pewarna buatan, melainkan dari bahan alami seperti daun suji dan kunyit.
Cenil dibuat dari tepung ketela pohon yang dikukus, lalu disajikan dengan taburan kelapa parut dan gula merah cair. Kini, cenil hadir dengan berbagai varian rasa seperti pandan, kopi, hingga cokelat. Bagi kamu yang ingin nostalgia, bisa menemukannya di beberapa titik di Jabodetabek, seperti sekitar Stasiun Juanda, Pasar Modern Bintaro, atau pedagang tradisional di Jagakarsa dan Cikokol.
Getuk: Camilan dari Masa Sulit yang Jadi Warisan Manis
Getuk lahir dari masa kelam, tepatnya saat penjajahan Jepang di Magelang. Kala itu, beras sangat langka, sehingga masyarakat beralih ke singkong sebagai sumber karbohidrat utama. Singkong yang dikukus kemudian ditumbuk, menghasilkan suara “getuk-getuk” yang akhirnya menjadi asal nama camilan ini.
Meskipun berawal dari keterpaksaan, getuk kini menjelma menjadi camilan manis yang penuh makna. Warnanya yang lembut dan rasanya yang gurih legit membuatnya tetap disukai lintas generasi.
Bagi kamu yang ingin mencicipinya, bisa mencari getuk goreng asli Haji Tohirin atau Getuk Trio Magelang di platform online seperti Tokopedia dan Blibli. Kalau ingin yang langsung jadi, mampir ke Getuk Goreng Asli Sokaraja di Tangerang Selatan juga bisa jadi pilihan.
Wedang Ronde: Hangatnya Akulturasi Budaya di Dalam Cangkir
Wedang Ronde adalah bukti lain dari perpaduan budaya kuliner. Minuman hangat ini berasal dari Tiongkok dengan nama asli tangyuan. Saat dibawa ke Indonesia oleh pedagang Tionghoa, masyarakat lokal menambahkan jahe dan gula jawa, menciptakan cita rasa khas Nusantara.
Kata “ronde” sendiri berasal dari bahasa Belanda rond, yang berarti bulat, menggambarkan bentuk bola-bola ketan di dalamnya. Minuman ini biasanya disajikan dengan tambahan kolang-kaling, roti tawar, dan kacang sangrai. Saat diminum hangat-hangat di malam hari, rasa jahe memberi sensasi menenangkan dan nostalgik.
Kini, wedang ronde tak hanya bisa ditemui di Yogyakarta atau Semarang, tapi juga di berbagai kedai tradisional di kota besar seperti Jakarta dan Bandung.
Di balik rasa manis, kenyal, dan hangat dari jajanan tradisional Indonesia, tersimpan kisah perjuangan dan perpaduan budaya yang membuatnya istimewa. Jadi, lain kali saat melihat pedagang cenil di pasar, atau bakpia di rak oleh-oleh, jangan ragu untuk membelinya. Karena setiap gigitan bukan sekadar rasa, tapi juga potongan kecil dari sejarah kuliner bangsa.