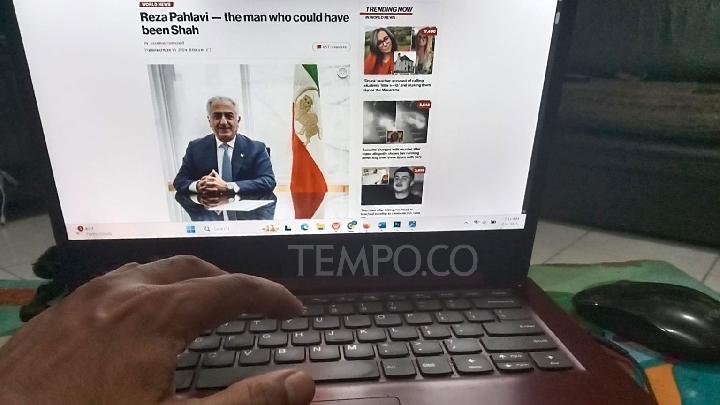Peran Musik dalam Kafe: Antara Selera dan Regulasi
Saya termasuk tipe orang yang tidak terlalu mempermasalahkan apakah sebuah kafe memiliki musik atau tidak saat berkunjung. Saya tetap bisa menikmati suasana kafe, baik itu dengan musik maupun tanpa. Yang paling penting bagi saya adalah kualitas makanan, minuman, atau kopi yang disajikan. Jika rasanya enak, tempatnya nyaman, atau cocok untuk berfoto, maka itu menjadi alasan utama untuk datang kembali.
Namun, tidak semua orang memiliki pandangan seperti saya. Banyak orang yang menganggap kafe tanpa musik kurang menarik. Bagi mereka, musik menjadi bagian dari pengalaman lengkap di kafe, terutama jika kafe tersebut dianggap sebagai bagian dari gaya hidup urban. Dalam konteks ini, musik sering kali dianggap sebagai elemen branding yang membantu menciptakan identitas unik sebuah kafe.
Tetapi ada juga yang merasa bahwa musik justru mengganggu. Misalnya, bagi mereka yang sedang bekerja, menghadiri rapat virtual, atau mengerjakan tugas kuliah yang membutuhkan ketenangan. Maka, muncullah konsep “kafe hening” atau “co-working caf”, yang menawarkan suasana tenang sebagai alternatif.
Kafe Sebagai Ruang Gaya Hidup
Dalam beberapa tahun terakhir, kafe tidak lagi hanya sekadar tempat minum kopi. Di Aceh, misalnya, banyak pemilik kafe berlomba-lomba menciptakan konsep unik, mulai dari nuansa retro, minimalis, hingga ruang keluarga yang nyaman. Kafe kini bukan hanya tempat ngopi, tetapi juga ruang sosial yang digunakan untuk bekerja jarak jauh, diskusi komunitas, atau sekadar berswafoto dan membuat konten media sosial.
Dengan adanya perubahan ini, musik menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan identitas kafe. Ada kafe yang memilih musik jazz untuk memberi kesan elegan, ada yang memainkan lagu pop santai, dan bahkan ada yang memutar musik indie eksperimental agar bisa membedakan diri dari yang lain.
Artinya, kehadiran musik di kafe mencerminkan selera pengunjung, tetapi tidak selalu mutlak. Ada yang lebih suka suasana tenang, sementara yang lain menganggap musik sebagai bagian dari pengalaman lengkap.
Dilema Royalti dan Solusi Alternatif
Masalah royalti dari lagu-lagu yang diputar di kafe menjadi dilema tersendiri bagi pemilik kafe. Di satu sisi, mereka ingin memberikan pengalaman yang menarik bagi pengunjung. Di sisi lain, mereka harus memenuhi kewajiban hukum untuk membayar royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Besaran tarif royalti biasanya sekitar Rp 60.000 per kursi per tahun untuk Royalti Pencipta dan Rp 60.000 per kursi per tahun untuk Royalti Hak Terkait, total Rp 120.000 per kursi per tahun. Namun, bagi kafe yang masih dalam skala UMKM, biaya ini bisa menjadi beban tambahan yang berpotensi meningkatkan harga makanan atau minuman.
Beberapa kafe memilih untuk tidak membayar royalti dan beralih pada alternatif lain. Misalnya, menggunakan platform musik yang bebas royalti, meskipun pilihan lagunya terbatas. Beberapa lainnya memilih memainkan musik live akustik atau mengundang musisi lokal sebagai bentuk promosi sekaligus penghargaan terhadap seniman.
Konsep Silent Caf: Ketenangan sebagai Daya Tarik
Di luar negeri, seperti di Jepang dan Korea, banyak kafe yang memilih konsep “silent caf”, yaitu kafe yang menjual ketenangan sebagai nilai tambah. Suasana hening dianggap lebih cocok bagi pengunjung yang butuh ruang kerja serius. Meski awalnya mungkin terasa asing, konsep ini bisa menjadi solusi yang layak dipertimbangkan.
Sebagai pengunjung yang tidak terlalu bergantung pada musik, saya tidak merasa terbebani dengan suasana hening. Namun, secara umum, musik di kafe bukan hanya tentang selera pengunjung atau beban royalti. Ini juga mencerminkan gaya hidup modern, regulasi hukum, dan penghargaan terhadap karya seni.
Secangkir kopi, apakah itu dinikmati dengan atau tanpa musik, tetap bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Yang terpenting, kafe harus tetap menjadi ruang yang nyaman bagi pengunjung, sekaligus memberi ruang bagi musisi yang karyanya ikut menghidupkan suasana.