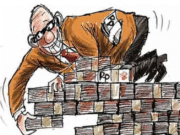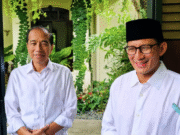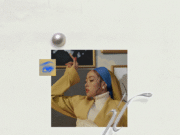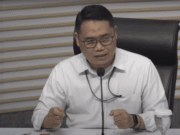Peran Masyarakat Pesisir dalam Menjaga Laut dan Kedaulatan Ekonomi
Diskusi yang berlangsung pada hari kedua Festival Media (Fesmed) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Benteng Ujung Pandang, Kota Makassar, menyoroti pentingnya peran masyarakat pesisir dalam menjaga laut sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi. Tema utama diskusi kali ini adalah “Masyarakat Pesisir Menjaga Laut, Berdaulat Pangan dan Ekonomi”. Acara ini menghadirkan pengalaman nyata dari nelayan Pulau Lanjukang yang telah menerapkan sistem buka-tutup area tangkap gurita sejak tahun 2022.
Ketua Forum Passibuntuluki, Erwin, menjelaskan bahwa praktik ini lahir dari kekhawatiran terhadap penurunan hasil tangkapan dan kerusakan terumbu karang. Ia mengatakan bahwa dulu, nelayan bisa mendapatkan gurita hanya dalam jarak 1-2 mil dari pantai. Namun kini, mereka harus pergi hingga 6-7 mil untuk mendapat hasil yang sama. Erwin juga menyebut bahwa mereka belajar dari praktik di Wakatobi dan dibantu oleh Yayasan Konservasi Laut Indonesia.
Dalam satu tahun, biasanya ada tiga lokasi buka-tutup dengan luas sekitar 600 meter persegi per lokasi. Meski awalnya gagal, program keempat dan kelima menunjukkan hasil positif. Dalam satu sesi, 20 nelayan bisa menangkap lebih dari 50 kilogram gurita hanya dalam waktu 1,5 jam.
Selain itu, inovasi juga datang dari Pulau Lakkai. Ketua Kelompok Merpati Putih, Nurjannah, menjelaskan bahwa kelompoknya kini mengolah hasil laut yang tidak laku di pasar menjadi abon dan sambal. Sebelumnya, mereka tidak memiliki kegiatan, tetapi setelah konservasi aktif, mereka mulai mengolah ikan dan gurita grade rendah agar memiliki nilai jual.
Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YKLI), Nirwan Dessibali, menekankan bahwa konservasi harus berbasis sosial, ekologi, dan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa gurita merupakan spesies unik yang cepat tumbuh dan ramah lingkungan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Guru Besar Antropologi Maritim Universitas Hasanuddin, Prof. Munsi Lampe, menilai sistem buka-tutup sebagai wujud kearifan lokal. Ia menekankan bahwa konservasi tidak hanya tentang lingkungan, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekonomi. Menurutnya, diperlukan kelembagaan nelayan, koperasi, industri olahan, serta pendidikan maritim berbasis budaya.
Diskusi juga membahas tantangan regulasi. Asad Asnawi dari Mongabay Indonesia menegaskan pentingnya perlindungan negara. Ia menyatakan bahwa upaya masyarakat di Lanjukang akan sia-sia jika negara tidak mengakui dan melindungi inisiatif mereka dalam kebijakan yang jelas.
Beberapa peserta menyoroti ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif, serta dampak tambang di Kendari. Diskusi akhirnya menyimpulkan bahwa diperlukan integrasi antara inisiatif lokal dan kebijakan nasional demi keberlanjutan ekosistem laut serta kemandirian pangan masyarakat pesisir.
Proyek Bioenergi: Solusi Hijau atau Alibi?
Diskusi publik bertajuk “Bioenergi dan Perampasan Ruang Hidup: Solusi Hijau atau Alibi?” mengupas narasi “hijau” di balik proyek bioenergi yang justru mengancam ruang hidup masyarakat. Diskusi ini berlangsung di Gedung E6, Benteng Ujung Pandang, Sabtu (13/9/2025), dengan menghadirkan tiga narasumber: Dominggus Mampioper (Tabloid Jubi), Amalya Reza (Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia), dan Fatwa Faturrahman (Forest and Society Research Group UNHAS).
Amalya Reza menegaskan bahwa proyek bioenergi hanyalah wajah baru dari eksploitasi. Di balik nama transisi energi, justru terjadi penggusuran besar-besaran. Ia menyebut istilah “energi hijau” sering menyesatkan. “Ini bukan solusi, ini hanya baju baru dari praktik lama,” ujarnya.
Dominggus Mampioper mengangkat kasus penanaman tebu di Papua yang mencaplok dua juta hektar lahan adat. Ia menyatakan bahwa masyarakat menolak karena hal tersebut berarti kehilangan akses tanah sekaligus identitas. Jika dipaksakan, ini bentuk alih fungsi lahan besar-besaran.
Sementara itu, Fatwa Faturrahman mengkritik cara pandang dominan terhadap hutan yang hanya dianggap kumpulan pohon. Ia menjelaskan bahwa hutan adalah identitas politik. Sejak kolonial, pengelolaan hutan di Indonesia digunakan untuk menyingkirkan masyarakat adat dan petani.
Menurut Fatwa, bioenergi lahir dari logika kapitalisme yang melihat alam sebagai komoditas transaksional. “Semangatnya sama dengan proyek hijau sebelumnya yang gagal karena mengabaikan aspek sosial,” tambahnya.
Dalam sesi tanya jawab, peserta menyoroti sikap pemerintah yang kerap mengabaikan suara masyarakat dan riset independen. Ketika ditanya soal rekomendasi akademik, Fatwa menegaskan bahwa sudah ada, tetapi pemerintah cenderung menolak. Mereka terus berada dalam posisi denial.
Seorang relawan Festival Media AJI menanyakan kemungkinan prediksi kapan hutan Indonesia habis. Meski belum ada data spesifik, para pembicara menyebut laju deforestasi yang terus meningkat sudah cukup memperlihatkan ancaman nyata: semakin sempitnya ruang hidup masyarakat adat dan petani.
Diskusi ini menutup dengan pesan utama bahwa proyek bioenergi yang diklaim sebagai solusi hijau justru berpotensi menjadi alibi baru bagi perampasan ruang hidup rakyat.