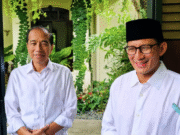Dari TikTok ke Etika Digital: Mengarahkan Ombak Teknologi Jadi Lautan Karakter untuk Generasi Z
Dinda, seorang remaja Indonesia biasa, sedang berusaha fokus menyelesaikan tugas kelompok. Namun, setiap kali jarinya berhenti mengetik, notifikasi dari TikTok dan Instagram mengajaknya “mampir” seperti teman yang sulit dilupakan. Swipe demi swipe, waktu terus berlalu, dan akhirnya Dinda sadar bahwa hidupnya lebih dipenuhi oleh algoritma daripada buku pelajaran. Suasana ini terasa sangat familiar bagi banyak Gen Z.
Bagi jutaan generasi Z seperti Dinda, dunia digital adalah rumah. Tapi rumah ini bisa menjadi tempat yang membentuk karakter mereka atau justru membuat mereka tenggelam. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa menyanyi bersama teknologi tanpa kehilangan jati diri?
Paradoks Gen Z: Jago Teknologi, Tapi Nyari Nilai Jadi Tantangan
Gen Z Indonesia, yang lahir setelah tahun 1997, dikenal sebagai “digital native”. Mereka mampu mengedit video 15 detik, menghafal lirik lagu viral dalam sehari, dan bahkan mencari jawaban kuis lebih cepat dari membuka buku. Namun di balik kemampuan hebat ini, ada sisi gelap yang membuat orang tua dan guru khawatir. Misalnya, minat baca yang hanya sepotong-sepotong, hati yang mudah goyah karena cyberbullying, hingga nilai seperti kejujuran yang mulai luntur di era AI.
Data dari Kemdikbud 2024 menunjukkan bahwa 68% siswa SMA mengaku pernah mencontek tugas menggunakan chatbot tanpa pikir panjang, dan 4 dari 10 remaja mengalami stres akibat tekanan “harus flawless” di media sosial. Meskipun demikian, teknologi tidak selalu menjadi musuh. Justru, ia bisa menjadi jendela emas untuk membentuk karakter, asalkan kita tahu cara memainkannya: bukan dengan memblokir, tapi dengan mengarahkan.
Teknologi Bukan Musuh: 3 Cara Keren Ubah Arus Jadi Kekuatan
Pertama, dari scroll menjadi soul: literasi digital menjadi “kitab suci” Gen Z. Bayangkan jika feed Instagram tidak hanya penuh dengan tantangan dance, tetapi juga konten #JujurItuKeren dari siswa SMA Negeri. Di sekolah tersebut, guru mengajak siswa membuat reels tentang kejujuran, misalnya, “Jika chatbot memberi jawaban salah saat ujian online, kamu pilih apa?” Program Sekolah Penggerak Kemdikbud ini meningkatkan kesadaran etika digital sebesar 52% dalam enam bulan. Teknologi menjadi “guru siluman” yang mengajarkan nilai lewat cara yang disukai Gen Z. Ada aplikasi Digital Character Tracker yang memberi feedback langsung, seperti: “Hari ini kamu tiga kali memuji teman di grup WA. Keep it up!”
Kedua, kelas terbalik, karakter jadi juara: TikTok menjadi guru dadakan. Di sebuah SMP Terpadu, metode flipped classroom membuat belajar karakter berbeda. Siswa menonton video empati selama 60 detik di rumah (dibuat guru dengan gaya TikTok), lalu di kelas mereka mendiskusikan kasus nyata: “Bagaimana merespons teman yang di-bully di grup chat?” Hasilnya, 90% siswa lebih berani melindungi korban cyberbullying, menurut survei sekolah. Ini membuktikan bahwa teknologi bisa memanfaatkan perhatian singkat Gen Z menjadi kekuatan. Konten tanggung jawab 60 detik, podcast toleransi 15 menit, atau game etika, semuanya menggunakan bahasa yang dimengerti Gen Z.
Ketiga, orang tua dan algoritma: duet tak terduga untuk membentengi karakter. Ibu Siti panik ketika mengetahui anaknya menonton konten tidak layak di YouTube. Tapi setelah mengikuti program Digital Parenting, dia mengubah parental control menjadi ajang ngobrol: “Mari nonton bersama, lalu kita bicarakan nilai apa yang bisa diambil.” Platform Keluarga Digital sangat membantu, orang tua menerima notifikasi jika anak terlalu sering membuka konten negatif, serta panduan ngobrol yang tidak membuat anak takut. Teknologi bukan lagi tembok, tapi jembatan untuk keluarga dan sekolah bersama-sama membentuk karakter.
Hati-Hati di Lautan: Teknologi Bisa Menolong, Bisa Juga Menikam
Namun, jangan lupa: teknologi memiliki dua wajah. Ada siswa yang nekad hack akun guru demi nilai, bukti bahwa tanpa kompas moral, teknologi hanya membuat kita nyasar. Oleh karena itu, literasi digital harus memiliki akar kuat dari nilai lokal, seperti sangkan paran (Jawa) atau adat basandi syarak (Melayu).
Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kemdikbud telah membuktikan hal ini: siswa Bali membuat digital story tentang Tri Hita Karana, siswa Aceh merancang aplikasi toleransi berbasis adat. Teknologi tidak mengganti karakter, tapi menjadi cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya.
Ke Lautan Karakter: Yuk Berlayar Bareng!
Setelah Dinda menyelesaikan tugas kelompoknya (tanpa menggunakan AI), ia sadar bahwa teknologi tidak menentukan siapa kita, tapi pilihan kita. Pesan untuk Gen Z? Anda bukan budak algoritma, Anda adalah kapten kapal sendiri. Caranya?
1) Sekolah harus mengubah smartphone menjadi senjata belajar karakter, bukan musuh.
2) Orang tua menjadi “digital mentor”, bukan hanya melarang.
3) Pemerintah mendorong Sekolah Penggerak hingga pelosok.
4) TikTok dan Instagram bekerja sama dengan Kemdikbud untuk membuat filter edukasi.
Penutup: Teknologi + Harapan = Masa Depan
Bayangkan ini yang terjadi: sekelompok siswa SMA merekam podcast soal kejujuran di era AI. Suara mereka gemetar, bukan karena takut, tapi semangat untuk memberi inspirasi. Gen Z tidak kehilangan karakter; mereka sedang mencari cara baru untuk menjaga nilai-nilai.
Teknologi itu seperti pisau, bisa menyakiti atau membantu, tergantung siapa yang memegangnya. Di tangan Gen Z yang didampingi cinta dan bijaksana, dia bisa menjadi “booster” untuk menjadi generasi jujur, kritis, dan peduli.
Jadi, bukan “bagaimana mematikan arus teknologi?”, tapi “bagaimana kita surfing bareng, sambil menjaga lampu karakter tetap menyala?”
Selamat berlayar, Gen Z. Dunia menunggu kapal Anda!